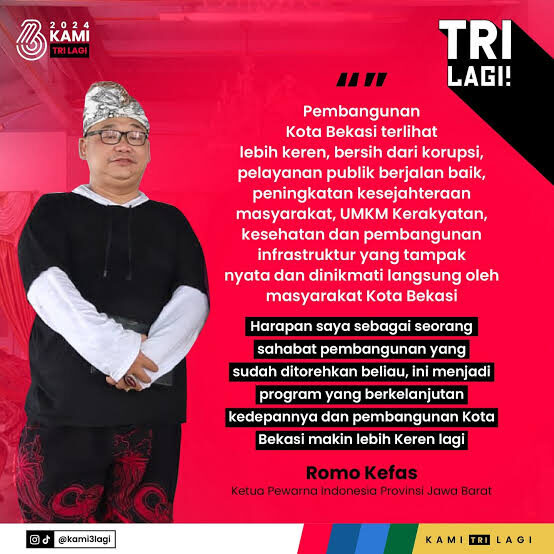Oleh: Ashiong P. Munthe, dosen STT Berita Hidup, STT IKAT Jakarta, Universitas Bunda Mulia, Universitas Multimedia Nusantara
Jakarta Diskusi publik bertajuk “Kolom Agama di KTP – Perlukah?” yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia, dan Simposium Setara Menata Bangsa menjadi momen reflektif yang penting. Di forum ini, diskusi tentang kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi menyingkap persoalan mendasar tentang relasi antara negara, iman, dan kemanusiaan.
Sebagai akademisi dan pengamat sosial yang berkesempatan hadir dalam forum tersebut, saya melihat isu ini bukan sebagai perdebatan teknis semata, melainkan sebagai soal pendidikan kebangsaan, sejauh mana kita telah belajar memahami manusia sebagai subjek yang utuh: makhluk rasional, sosial, dan spiritual.
Identitas dan Pendidikan Kewargaan
Kolom agama dalam KTP telah lama menjadi simpul sensitif dalam struktur sosial Indonesia. Ia bukan sekadar kolom data, melainkan simbol identitas yang menandai posisi seseorang di tengah masyarakat majemuk. Dari sisi pendidikan kewargaan, hal ini memperlihatkan bagaimana negara masih memandang warganya melalui kategori yang bersifat homogen dan normatif.
Padahal, dalam sistem pendidikan modern, identitas seharusnya dipahami secara reflektif: bukan label yang diberikan dari luar, melainkan kesadaran diri yang tumbuh dari dalam. Ketika negara menegaskan keharusan mencantumkan agama tertentu, maka proses pendidikan kewargaan berubah menjadi proses penyeragaman. Inilah yang oleh banyak sosiolog disebut sebagai asimilasi administratif, yakni ketika keberagaman spiritual dipaksa masuk ke dalam kotak birokrasi.
Di titik ini, pendidikan publik perlu menanamkan cara berpikir baru: bahwa identitas keagamaan tidak boleh menjadi alat kategorisasi sosial, melainkan bahan pembelajaran tentang kemanusiaan.
Asimilasi dan Reduksi Spiritualitas
Sejarah Indonesia mencatat bagaimana pada masa Orde Baru, negara menerapkan logika “penyeragaman iman” dengan hanya mengakui lima agama resmi. Banyak penghayat kepercayaan terpaksa berlindung di bawah salah satu agama besar agar tetap diakui oleh sistem.
Fenomena ini, jika dibaca secara filosofis, merupakan bentuk reduksi spiritualitas, iman yang semestinya menjadi wilayah kesadaran batin, dijadikan instrumen administratif. Dalam bahasa rasional, iman dikompresi menjadi data statistik; dalam bahasa etika, spiritualitas dikorbankan demi ketertiban negara.
Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK), salah satu pembicara dalam forum tersebut, dengan jernih mengakui bahwa situasi itu pernah memberi “tambahan umat” bagi Hindu Dharma, namun ia menolak melihatnya sebagai keuntungan. Baginya, kebenaran iman tidak bisa diukur dari angka. Pernyataannya, lebih baik sedikit tapi sejati daripada banyak tapi semu, adalah pelajaran moral yang kuat. Ia menegaskan bahwa iman yang otentik tidak lahir dari statistik, tetapi dari kesadaran diri yang bebas.
Dalam konteks hukum, konstitusi kita sesungguhnya sudah menyediakan kerangka rasional yang jelas. Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menegaskan hak penghayat kepercayaan untuk dicantumkan dalam administrasi kependudukan.
Namun, sebagaimana kerap terjadi, pendidikan konstitusional masyarakat tidak tumbuh secepat perubahan hukum. Diskriminasi masih ada. Kolom agama, alih-alih menjadi alat identifikasi, sering kali berubah menjadi alat kategorisasi sosial. Di sini kita menemukan jurang antara rasionalitas konstitusi dan emosionalitas sosial.
Oleh karena itu, pembelajaran kewargaan modern harus menanamkan kesadaran bahwa konstitusi bukan hanya teks hukum, tetapi juga etika bersama. Hanya ketika warga memahami konstitusi secara filosofis — sebagai pernyataan martabat manusia, bukan sekadar pasal hukum — barulah kita bisa berbicara tentang kebebasan yang sejati.
Humanisme dan Rasionalitas Negara
Salah satu argumen menarik datang dari AWK, yang melihat kolom agama memiliki fungsi kemanusiaan dalam situasi darurat: memastikan jenazah diperlakukan sesuai keyakinannya. Pandangan ini mengandung nilai humanisme yang dalam, bahwa negara harus menghormati spiritualitas manusia, bahkan setelah ia meninggal.
Namun, justru di titik kemanusiaan inilah paradoks muncul. Jika kolom agama digunakan untuk menjamin kemanusiaan, maka negara harus memastikan kolom itu tidak menjadi sumber ketidakmanusiawian. Kasus-kasus diskriminatif, seperti kesulitan minoritas mengakses pelayanan publik, memperlihatkan bagaimana instrumen administratif bisa berubah menjadi alat eksklusi.
Di sinilah pendidikan moral publik menjadi penting: mengajarkan bagaimana administrasi tidak boleh menindas nilai kemanusiaan yang hendak dilayaninya. Rasionalitas negara harus berpadu dengan empati sosial.
Kementerian Agama dan Rasionalitas Struktural
Penanggap lain, Yohanis Henukh, mengingatkan bahwa selama negara masih memiliki Kementerian Agama, penghapusan kolom agama belum realistis. Pandangan ini, meskipun terkesan birokratis, justru mencerminkan rasionalitas sistemik. Negara tidak bisa memutus satu simpul tanpa mereformasi keseluruhan jaringan hukum dan kelembagaan.
Dengan kata lain, penghapusan kolom agama bukan hanya keputusan moral, tetapi proyek pendidikan sistemik, bagaimana negara belajar menjadi sekuler secara administratif tanpa kehilangan etika spiritualnya. Ini bukan sprint, melainkan maraton peradaban.
Politik Angka dan Krisis Makna
Dalam banyak kebijakan publik, data agama sering dijadikan dasar pembagian anggaran atau representasi kekuasaan. Di sinilah muncul fenomena politik angka, ketika iman dipolitisasi menjadi statistik.
Secara filosofis, ini adalah bentuk lain dari krisis makna dalam keberagamaan modern. Ketika agama dinilai dari jumlah penganut, spiritualitas kehilangan dimensi eksistensialnya. Pendidikan agama harus mengoreksi logika ini: agama bukan kompetisi numerik, melainkan proses pembentukan nilai kemanusiaan.
Pendidikan Toleransi dan Rekognisi
Langkah maju telah diambil ketika penghayat kepercayaan ditempatkan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Kementerian Agama. Secara simbolik, ini adalah bentuk pendidikan inklusif: spiritualitas diperlakukan sebagai ekspresi kebudayaan, bukan institusi politik.
Para penghayat merasa lebih tenang di bawah naungan pendidikan, bukan politik. Mereka tidak menuntut hak istimewa, hanya pengakuan dan penghormatan. Sikap ini memberi pelajaran penting: spiritualitas yang matang tidak mencari validasi negara. Dalam konteks ini, justru agama-agama besar perlu belajar dari mereka tentang keimanan yang bebas dari ego politik.
Menuju Rasionalitas Administrasi yang Beradab
Dari perspektif teknologi kependudukan, tentu negara bisa saja menyimpan data agama secara internal tanpa mencantumkannya di KTP. Namun, secara sosial, kita belum siap. Literasi keberagamaan masyarakat masih rentan terhadap kecurigaan dan stereotip.
Karena itu, langkah yang paling mendidik bukan menghapus kolom agama secara tiba-tiba, tetapi mendidik publik untuk memaknainya secara benar. Kolom agama harus dimurnikan fungsinya: bukan sebagai alat kategorisasi, tetapi pengakuan terhadap martabat iman seseorang. Negara wajib memastikan data itu tidak digunakan untuk menilai siapa yang “berbeda,” melainkan untuk menjamin hak spiritual tiap warga negara.
Pendidikan Kemanusiaan dalam Administrasi Negara
Polemik tentang kolom agama mengajarkan satu hal mendalam: bahwa pendidikan kebangsaan sejati bukan hanya tentang membaca undang-undang, tetapi tentang memahami manusia.
KTP adalah selembar kartu yang sederhana, namun di dalamnya tersimpan sejarah panjang tentang bagaimana negara belajar mengenali warganya — bukan hanya sebagai entitas hukum, tetapi sebagai makhluk beriman dan berpikir.
Mungkin suatu hari nanti, ketika bangsa ini telah matang dalam literasi spiritual dan rasionalitas politik, kolom agama tak lagi diperlukan. Namun sampai saat itu tiba, kolom itu masih bisa berfungsi sebagai cermin pembelajaran moral, sejauh mana kita mampu memperlakukan perbedaan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih manusiawi.